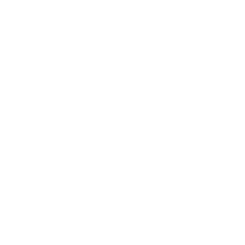‘Aisyiyah Soroti Tantangan Gerakan Perempuan di Indonesia pada Australasian Aid Conference 2025
Canberra — Kemajuan kesetaraan gender di kawasan Asia dan Pasifik yang mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, menjadi sorotan utama dalam sesi plenary Australasian Aid Conference (AAC) 2025 yang digelar di Acton Theatre, Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), Canberra, Jumat (5/12/2025). Forum internasional ini diselenggarakan setiap tahun yang melibatkan mitra-mitra Pembangunan Australia, akademisi, peneliti, NGO, pemerintahan dan praktisi Pembangunan.
Dalam salah satu plenary yang menghadirkan para pemimpin pemikiran, praktisi pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil membahas tantangan meningkatnya konservatisme, hipermaskulinitas politik, serta melemahnya komitmen kebijakan terhadap keadilan gender. Dalam sesi plenary dengan model talkshow ini, Tri Hastuti Nur Rochimah, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, memaparkan gerakan perempuan di Indonesia telah memperoleh banyak capaian mulai dari perjuangannya selama ini.
Beberapa capaian antara lain Pembentukan Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, tindakan afirmatif terkait representasi perempuan di parlemen, cabang eksekutif sebesar 30%, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, Peninjauan Yudisial terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7a tentang usia perkawinan dan pengesahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Namun memang di tengah berbagai capaian tersebut, muncul gerakan melawan perjuangan kesetaraan gender ini dari beberapa kelompok konservatif di Indonesia baik organisasi perempuan maupun tokoh agama konservatif. Kelompok ini melihat gerakan perempuan Indonesia sebagai gerakan yang Tunggal; dan mereka menggunakan gerakan anti feminisme.
“Gerakan anti-feminisme di Indonesia bekerja di berbagai level, mulai dari nilai-nilai keluarga, norma sosial yang diperkuat oleh tokoh agama yang konservatif dan tokoh masyarakat, beberapa kebijakan pemerintah, hingga media konvensional dan digital yang dimanfaatkan oleh kelompok ini,” ujar Tri Hastuti.
Ia mencontohkan bagaimana perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga, bahkan ketika perempuan mengalami kekerasan, mereka menjadi pihak yang disalahkan. Meskipun UU PKDRT sudah berusia 21 tahun namun angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. “Perempuan sering dibebani kewajiban menjaga keutuhan keluarga, bahkan ketika mereka menjadi korban kekerasan. Ini menunjukkan bagaimana nilai patriarki masih dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Representasi tersebut terus direproduksi melalui iklan, ceramah keagamaan baik secara langsung (offline) maupun di media konvensional, serta konten media sosial yang menormalisasi peran domestik perempuan sebagai tanggungjawab perempuan semata dan relasi kuasa yang timpang dalam keluarga. Perempuan mengalami beban ganda bahkan triple burden.
Selain itu, Tri Hastuti menyoroti maraknya konten digital yang menyudutkan perempuan dengan kemandirian ekonomi dan partisipasi di ruang publik. Perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri kerap dituduh melanggar kodrat, pemahaman kodrat yang salah, merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan sering dianggap menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian ditimpakan pada perempuan bahwa dikarenakan sudah mandiri secara ekonomi maka perempuan mengajukan cerai. Cara berpikir seperti ini membungkam perempuan, dan memposisikan perempuan dalam posisi yang selalu disalahkan.
“Perempuan yang memiliki agensi ekonomi dan akses ke ruang publik sering kali disalahkan atas instabilitas keluarga dan dianggap menentang nilai-nilai sosial yang mapan,” tegasnya.
Menurutnya, titik balik terhadap perjuangan kesetaraan gender ini menguntungkan kelompok-kelompok konservatif, termasuk sebagian organisasi perempuan konservatif, tokoh agama konservatif, aktor politik yang mendapatkan manfaat dari kondisi ini, serta elit komunitas yang berkepentingan mempertahankan struktur patriarki yang timpang ini.
Meski demikian, Tri Hastuti menegaskan bahwa gerakan perempuan di Indonesia terus melakukan perjuangan melalui strategi yang beragam dan berjangka panjang. ‘Aisyiyah, bersama jejaring masyarakat sipil, mendorong penguatan gerakan akar rumput, advokasi kebijakan dari tingkat desa hingga nasional, serta pengembangan tafsir keagamaan progresif yang berkeadilan gender. Gerakan perempuan di Indonesia tidak boleh elitis, namun harus membumi menguatkan gerakan di tingkat local selain nasional; dan sinergitas antara akademisi dan aktivis gerakan perempuan.
“Kami memperkuat kepemimpinan perempuan, melakukan advokasi kebijakan lintas level, dan mengembangkan interpretasi keagamaan yang menjamin hak-hak dasar perempuan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keterlibatan perempuan Muhamamdiyah yaitu Aisyiyah dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berkontribusi pada lahirnya fatwa-fatwa progresif seperti pelarangan perkawinan anak, kewajiban pencatatan perkawinan, pelarangan nikah siri serta penolakan terhadap praktik sunat perempuan karena sifatnya yang membahayakan.
Sesi panel AAC 2025 ini dipandu oleh Dr Nicola Nixon, Direktur Senior Bidang Tata Kelola di The Asia Foundation, serta menghadirkan pembicara lain, yakni Michelle Reddy, Co-Lead Kemitraan dan Mobilisasi Sumber Daya dari Pacific Feminist Fund, dan Susanne Legana, CEO Plan International Australia. Para panelis membahas strategi kepemimpinan perempuan, keterlibatan laki-laki yang transformatif, serta penguatan gerakan lokal berperspektif gender untuk menghadapi gelombang kemunduran kesetaraan gender di kawasan Asia dan Pasifik.